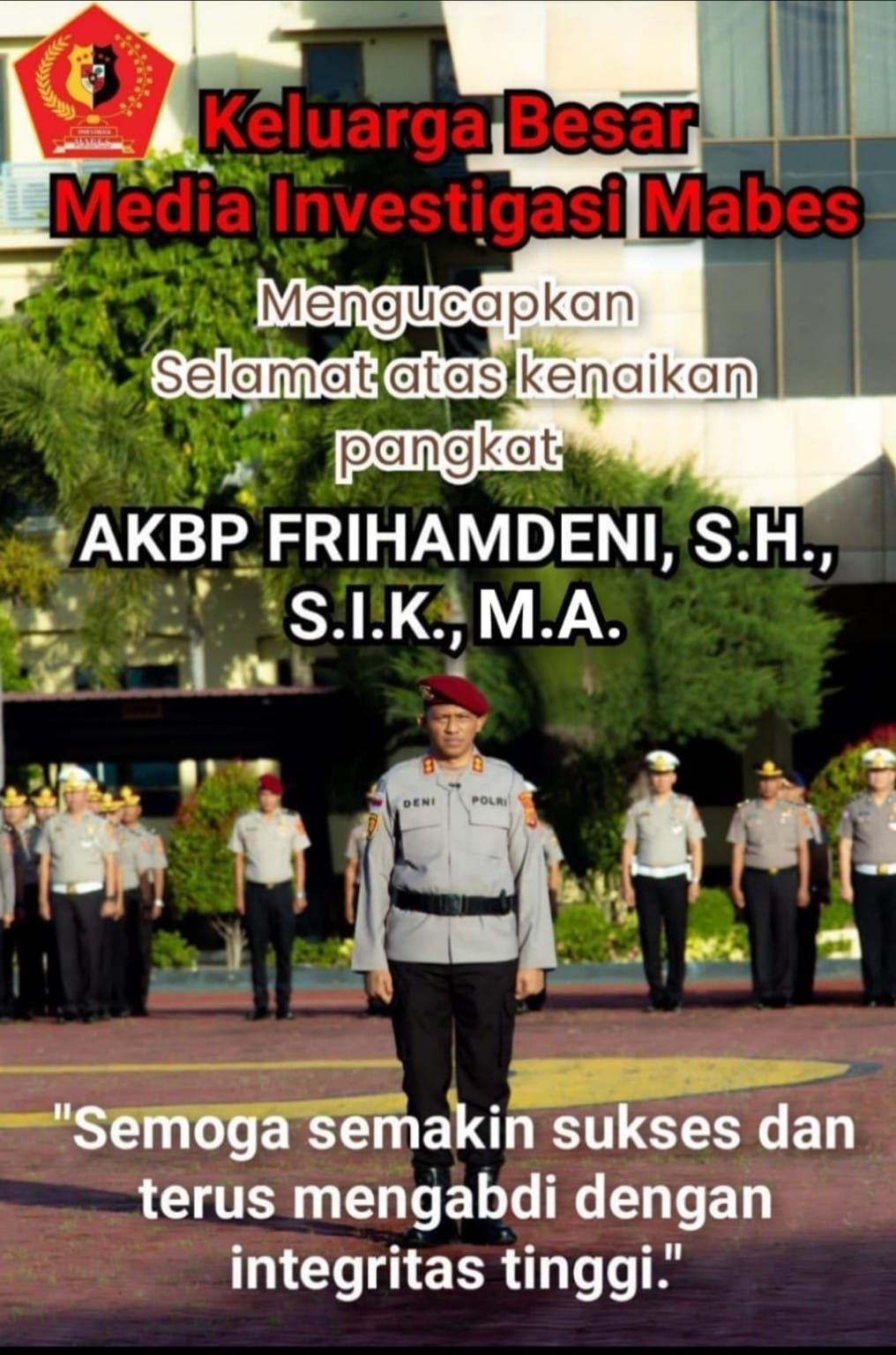MEDIAINVESTIGASIMABES.CO.ID | JAKARTA – Apa yang dimaksud dengan logika dan penalaran hukum? Bagaimana hubungan kedua hal tersebut?
Arti Logika dan Penalaran
Sebagai langkah awal mempelajari ilmu logika hukum, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu definisi dari logika. The Liang Gie dalam bukunya Dictionary of Logic (Kamus Logika) menjelaskan bahwa logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul atau dikenal dengan correct reasoning. Sementara itu, menurut Mundiri, logika merupakan sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah.
Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Logos berarti: sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, pikiran, kata, atau ungkapan lewat bahasa. Sedangkan logikos adalah sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa.
Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut logike episteme atau dalam bahasa latin disebut logica scientia yang berarti ilmu logika, namun sekarang kita kenal dengan sebutan logika saja.
Berbeda dengan logika, penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap terminologi dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran. Pada dasarnya, pengertian, proposisi, dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan, sebab penalaran mensyaratkan proposisi dan proposisi mengandaikan pengertian. Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi.
Pada hakikatnya proposisi adalah pendirian, pernyataan, atau pendapat tentang sesuatu hal, dan terhadap proposisi dapat dikenakan penilaian benar atau salah.
Penalaran Hukum
Penalaran hukum adalah penerapan prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau legal reasoning tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam pengertian lain, tidak ada penalaran hukum di luar logika, dan tidak ada penalaran hukum tanpa logika.
Pada dasarnya, penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika merupakan ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan hukum, atau sebaliknya ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Dengan adanya penalaran hukum, hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja, hukum juga bukan sekedar norma atau aturan yang ditetapkan otoritas tertinggi dan wajib diikuti. Akan tetapi, hukum harus didasari pada sifat logis, sebab logis adalah salah satu karakter atau sifat dasar hukum.
Penalaran hukum juga dapat diartikan sebagai cara lawyer dan hakim dalam berbicara mengenai hukum di ruang publik. Istilah ini merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli berbagai aktivitas dalam dunia hukum, antara lain proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum, identifikasi kasus, interpretasi, evaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum, penerapan hukum dalam kasus, penyusunan pertimbangan, penyusunan argumen, opini atau pendapat hukum. Perlu diketahui bahwa semua aktivitas tersebut didasarkan pada cara bernalar atau berlogika yang tepat, alias logika hukum.
Legal reasoning merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai peneliti hukum, sebab tanpa adanya pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seorang peneliti akan kehilangan arah dan menemui kesulitan dalam mensistematisasikan bahan hukum, sehingga mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan penelitiannya.
Selain menggunakan terminologi legal reasoning, penalaran hukum juga dikenal sebagai argumentasi hukum. Menurut Golding, terminologi legal reasoning dapat digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi hukum yang melandasi suatu keputusan. Artinya, legal reasoning dalam arti sempit menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yakni hubungan antara reason berupa pertimbangan, alasan, putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan lainnya yang mendukung putusan tersebut.
Jenis Argumentasi Hukum
Argumentasi hukum merupakan kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, transaksi perdagangan, dan lainnya. Selain itu, pencarian dasar hukum juga bisa dilakukan pada kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, maupun administrasi, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.
Kemudian, para ahli teori hukum mengklasifikasikan 3 (tiga) pengertian dari argumentasi hukum, yaitu:
- Mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi.
- Argumentasi dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil, atas perkara yang terjadi.
- Argumentasi mengenai putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua aspek.
Terdapat 2 (dua) macam model argumentasi hukum antara lain: - Systemic legal reasoning, yakni kegiatan yang bercorak normatif, yang dibangun di atas sistem penalaran hukum, dan mengandung unsur rasionalisme, positivisme hukum apriori, analisa, deduksi, koherensi, penelitian hukum normatif, dan berpikir sistemik.
- Critical legal reasoning, yakni kegiatan yang unsurnya terdiri dari empirisme, historikal, yurisprudensi, aposteriori, sintesa, induksi, korespondensi, penelitian hukum sosiologis dan berpikir kritis.
Kesimpulannya, logika merupakan cabang ilmu yang penting dipahami oleh peneliti hukum. Sebab, logika adalah bagaimana cara berpikir secara tepat, memikirkan ide, gagasan, dan opini hukum yang pada dasarnya harus bersifat logis juga. Logika memiliki hubungan yang erat dengan penalaran hukum. Eksistensi penalaran hukum menunjukkan bahwa hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja, melainkan hukum harus didasari pada sifat logis. Sebagai catatan, penalaran hukum juga kerap digunakan dengan menggunakan terminologi lain yakni legal reasoning dan argumentasi hukum.
Referensi: - Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Vol. 5, No. 1, 2017;
- Fransiska Novita Eleanora, Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat, Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018;
- Muhamad Rakhmat, Logika Hukum, Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2015;
- Musa Darwin Pane (et.al), Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum, Bandung: Penerbit Cakra, 2018;
- Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, 2017.
- Sosiologi Hukum Ruang Lingkup, Objek, & Karakteristiknya
- Pengertian Sosiologi Hukum
- Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum diperkenalkan oleh Aguste Comte, yakni sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan Secara etimologis, sosiologi berasal dari Bahasa Latin “socius” yang artinya kawan, serta Bahasa Yunani “logos” yang artinya kata atau berbicara. Jika digabungkan, maka sosiologi merupakan ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. Aguste Comte juga menegaskan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis.
- Sedangkan menurut Pitirim Sorikin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial seperti gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dengan gejala lainnya.
- Sosiologi hukum menurut sejarah diperkenalkan pertama kali oleh Anzilotti, yang lahir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum dan sosiologi. Sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, dalam sosiologi hukum, hukum hanya merupakan salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa sistem sosial lainnya dalam masyarakat memberi arti dan pengaruh terhadap hukum itu sendiri.
- Sosiologi hukum adalah teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum tersebut dapat dipelajari dengan 2 (dua) cara antara lain:
- Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan;
- Menjelaskan kenyataan kemasyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum.
Menurut Meuwissen, sosiologi hukum adalah hukum positif yang berlaku, dalam pengertian lain, isi dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai waktu dan tempat dan dipengaruhi faktor kemasyarakatan. Sedangkan menurut Alvin S. Johnson, sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum dimulai dari hal nyata, seperti organisasi baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi atau kebiasaan, dan juga dalam materi dasar seperti struktur ruang dan kepadatan lembaga hukum secara demografis.
Menurut Satjipto Rahardjo, objek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum yaitu mengkaji pengorganisasian sosial hukum. Objek sasaran pada sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, polisi dan advokat.
Dari berbagai doktrin yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial. Sosiologi memiliki perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya, sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi.
Sosiologi hukum menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Karakteristik sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terkait praktik hukum oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Jika praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum, dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut.
Kemudian, sosiologi hukum juga menguji keabsahan empiris dari peraturan atau pernyataan hukum. Sebagai contoh, jika hal tersebut dirumuskan dalam suatu pertanyaan, yakni: - Bagaimana peraturan tersebut dalam kenyataan?
- Apakah kenyataan memang seperti tertulis pada bunyi peraturan?
Terdapat suatu perbedaan antara kedua pendekatan tersebut, yang pertama bahwa menerima saja apa yang tertera dan tertulis di aturan hukum, sedang yang kedua menguji dengan data empiris.
Ruang lingkup sosiologi hukum secara spesifik mencakup 2 (dua) hal, yaitu: - Dasar-dasar sosial dari hukum, misalnya hukum nasional Indonesia yang dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
- Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, misalnya UU Penanaman Modal terhadap gejala ekonomi, UU Pemilu terhadap gejala politik, UU Hak Cipta terhadap gejala budaya, UU Pendidikan Tinggi terhadap gejala pendidikan, dan lainnya.
Kemudian, yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau dikenal dengan Government Social Control. Dalam objek tersebut, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.
Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, karakteristik sosiologi hukum meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut: - Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat.
- Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial.
- Hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial serta budaya.
Kesimpulannya, sosiologi hukum adalah ilmu yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum. Selain itu, karakteristik atau ciri khas dari sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum warga masyarakat.
Dasar Hukum: - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Referensi:
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al), Sosiologi Hukum, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017;
- Yesmil Anwar (et.al), Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Grasindo, 2011;
- Yusuf Daeng, Sosiologi Hukum, Pekanbaru: Alaf Riau, 2018.( Red/Arthur)